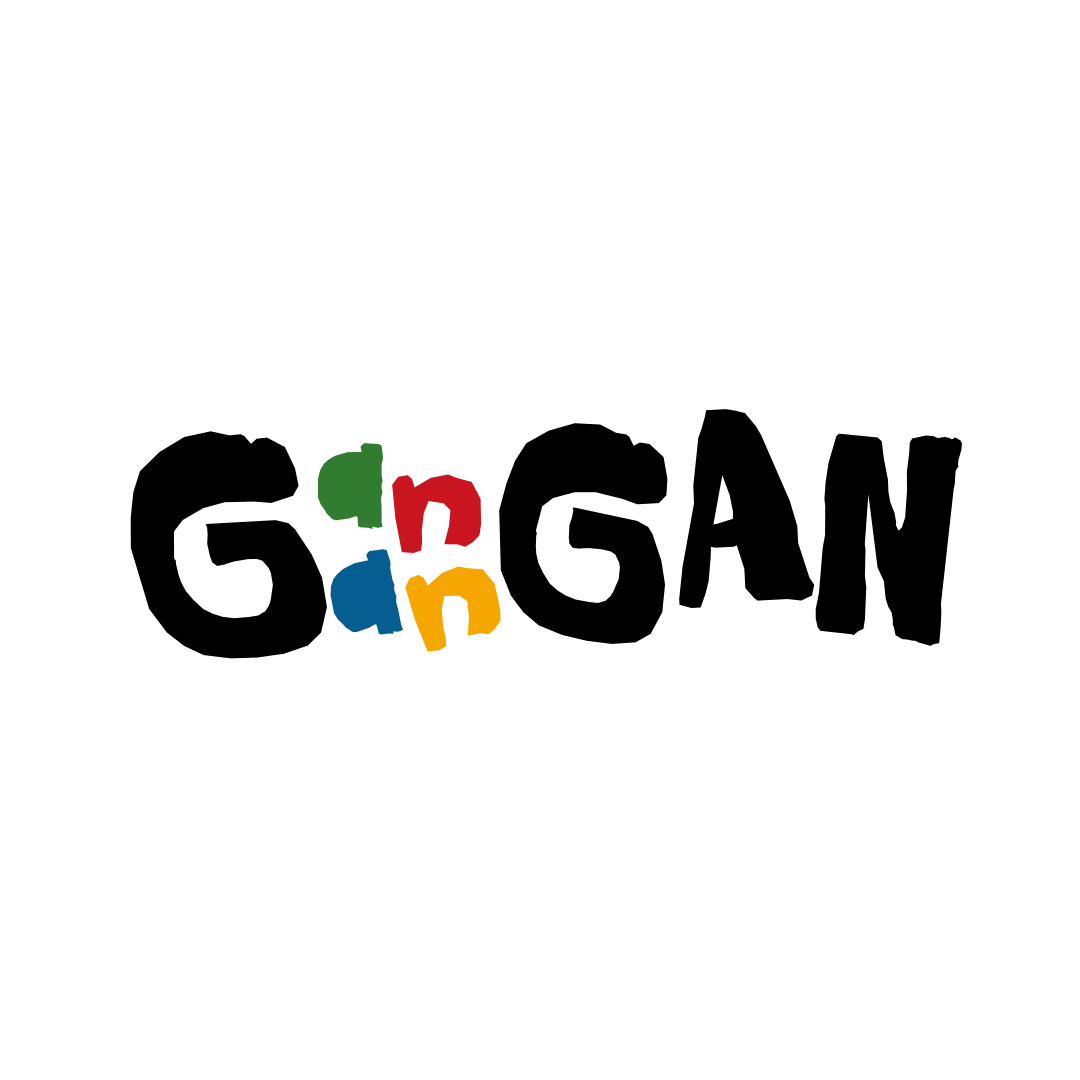Mulanya kami merasa lebih senang menceritakan apa yang menurut kami menyenangkan melalui media sosial saja, namun agaknya menuliskannya di dalam blog ini akan memudahkan banyak hal; harapannya.
Asal Muasal
Kami terdiri dari beberapa orang yang tersebar di beberapa titik di Jogja dan Jawa Tengah, baru-baru ini kami punya teman baru di Jakarta. Pada mulanya, @gang.gang.an dibuat di Instagram hanya didasari kami yang suka jalan-jalan di kampung-kampung kami, lalu kami merasa IGS akun pribadi hanya memungkinkan kami untuk melihat dokumentasi main kami selama 24 jam saja. Pada waktu itu, kami tidak menemukan fungsi lain dari akun instagram tersebut selain dokumentasi jalan-jalan kolektif sempit kami.
Seiring berjalannya waktu, beberapa rekan bergabung. Penyebabnya tak lain dan tak bukan adalah kesamaan hobi jalan kaki. Selain menjadi sarana kami berolahraga selain pusing bekerja, juga sebagai ajang untuk mengenal kota Jogja dan Wonosobo lebih baik. Kebetulan dua kota tersebut adalah domisili dari mayoritas “admin”.
Ketika berjalan dengan orang yang berbeda-beda, dengan latar sosial, pendidikan, dan preferensi yang beragam, kami pun menemukan bahwa hal-hal tersebut mempengaruhi corak pandang kami ketika berjalan-jalan di kampung, terutama kampung kota. Yang lebih menyukai interaksi dengan orang, dia akan cenderung banyak mengobrol dengan warga lokal. Yang suka dengan fotografi lebih banyak mengambil detail-detail yang menarik menyoal gang, pun dengan mereka yang suka dengan kuliner, otomatis akan mengulik kuliner di sekitar. Dari sanalah muncul gagasan, bagaimana kalo kegiatan sederhana ini kita beri value?
Apa yang kami percaya?
Cita-cita kami cukup sederhana, kami ingin hasil dokumentasi kami ketika berjalan dan melakukan pengarsipan (visual) ini menjadi rujukan buku IPS sejarah kota, di masa mendatang. Alasan yang cukup absurd namun bagi kami cukup berdasar.
Kami tentu sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau historis, masa lalu bagi kami masih sangat seksi. Sebelum Ganggangan menjelma menjadi “walking tour” menurut on the spot, kami mengikuti beberapa walking tour yang ada di kota Jogja dengan harapan mendapatkan cerita-cerita menarik soal kota Jogja. Bagi kami waktu itu, kesejarahan terasa menyenangkan sampai salah satu dari kami menyeletuk,
“aku lahir dan tinggal di Jogja hampir 30 tahun, bisa ngga sih aku jadi saksi dan sumber sejarah itu?”
Bisa jadi benar, kota ini mengalami perubahan yang sangat cepat hanya dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Pertanyaan lalu kami lanjutkan,
“Kalo semua membahas era penjajahan, lantas siapa yang akan mendokumentasikan hal-hal di saat cappucino cincau menjadi comfort food mahasiswa UIN?”
Hal sederhana yang kami lakukan ini menjelma menjadi sesuatu yang penting (minimal bagi kami sendiri). Alih-alih menggali informasi masa lalu melalui jurnal ataupun cerita-cerita masa lalu, kami pun akhirnya lebih fokus kepada apa yang sedang terjadi di depan mata kami, di masa sekarang. Yang mulanya kami lakukan sendiri di kampung sendiri, pelan kami mencoba iseng untuk berjalan di kampung orang lain. Kami sangat paham apa yang kami lakukan akan terlihat aneh bagi warga di kampung tempat kami berjalan, oleh karena itulah kami berusaha mencari tameng rasa malu dengan sebisa mungkin mengajak warga sekitar untuk bergabung. Selain menjadi sebagai salah satu bentuk tata krama, juga kami sering mendengar cerita-cerita menarik yang hanya akan kami ketahui ketika kami tinggal di daerah tersebut dalam waktu yang lama. Tentu tidak ada siapapun yang lebih relevan menceritakan suatu tempat dibanding dengan warga lokal. Hal ini masih kami pertahankan sampai sekarang.
Selain mengajak warga lokal, kami pun membatasi jumlah peserta yang ikut berjalan bersama kami. Di setiap trip, kami biasanya hanya menerima 2-4 orang dari pihak di luar “admin”, sementara kami membatasi diri kami sendiri dengan hanya membawa 2-3 personil. Jadi di setiap trip, biasanya hanya terdiri dari 4-7 orang. Tentu akan selalu ada pengecualian, terutama ketika ada warga lokal yang ingin bergabung. Kami tidak membatasi jumlah warga lokal yang ingin ikut, ha wong ning kampung e dewe. Selain itu juga kami akan menambah jumlah peserta ketika kami benar-benar paham bahwa suatu daerah yang ingin kami jelajahi sudah familiar dengan turis, di area Tamansari atau Kauman misalnya. Itu pun biasanya tidak pernah lebih dari 15 orang.
Kapan kami mengadakan trip? Sesuka kami. Kami lebih sering berjalan sendiri-sendiri dibanding mengadakan open trip (bisa dicek poster open trip di satu tahun terakhir). Kami sengaja membatasi jumlah open trip, pun sekalinya membikin trip, di hari-hari kerja. Hal ini adalah salah satu filtrasi pertama untuk menyaring siapa yang memang berniat untuk ikut, dengan memahami value-value yang kami pegang. Untuk ikut pun, kami akan memberikan beberapa pertanyaan sederhana, namun menjadi bahan pertimbangan kami untuk memilih. Kami tidak sembarang mengajak orang karena kami sadar diri tidak ada yang bisa mengendalikan pikiran dan perilaku individu lain. Sesama “admin” saja kami sering berantem.
Kami tidak sembarang memilih daerah untuk bertamu. Biasanya kami akan jalan sendiri dulu dua atau tiga kali sebelum kami menilai apakah daerah tersebut oke untuk dibikinkan open trip atau tidak. Oke di sini dalam artian kami dinilai mengganggu atau tidak.
Isu eksploitasi dan “ghetto tourism”
Topik ini sudah jauh-jauh kami bahas sebelum kami mulai membuka open trip untuk pertama kalinya. Kami tidak pernah menyangkal bahwa kami menjadikan jalan kaki di gang salah satu cara kami untuk rehat. Apa yang kami lakukan tentu sangat erat kaitannya dengan isu eksploitasi dan “romantisasi kemiskinan”.
Kami memilih gang sebagai tempat bermain kami sesederhana dikarenakan kami juga dekat dengan gang itu sendiri. Saya yang menulis tulisan ini lahir dan hidup di kawasan padat di kota Jogja, di tengah gang padat area Bausasran. Admin lain tinggal di kompleks perumahan sederhana di lereng gunung di daerah Garung, Wonosobo. Admin lainnya lagi minoritas Tionghoa yang hobi menanam tanaman aneh di gang karena tidak memiliki lahan yang cukup di rumah sendiri di Jakarta. Kami merasa dekat dengan gang bukan semata memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang sangat eksotis, kami adalah bagian dari kemiskinan struktural itu sendiri; yang lalu berusaha membangun kebahagiaan dengan memperhatikan detail kecil di sekitar kami. Itulah mengapa kami menjadikan gang sebagai topik utama pembahasan kami, bukan di agenda berjalannya. Mau jalan, mau bersepeda, mau motoran, bebas. Sesederhana itu.
Kami tidak suka disebut sebagai walking tour, karena kami tidak berperan sebagai tour guide. Kami tidak menceritakan hal-hal adiluhung, apa yang kami ceritakan adalah hal personal yang kami alami sendiri, selebihnya kami sangat berharap partisipasi aktif dari peserta trip. Kami berusaha membangun relasi komunikasi dua arah, selain bisa ada informasi baru bagi kami, kami berharap peserta trip bisa membantu usaha kami untuk mengenang tempat kami berjalan. Kawasan kampung kota, terutama, bertumbuh terlalu cepat.
Berbayar? Tentu tidak. Apa yang kami lakukan bukanlah hal spesial, dan kami bukan pionir. Apa yang kami lakukan itu sangat biasa dan sepele, dan kami tidak cukup tega memberikan pengalaman bermain yang biasa ini tarif, seberapapun nominalnya. Timbal balik yang kami harapkan sebenarnya hanyalah tulisan dan semangat untuk mengajak teman terdekat bermain di lingkungan terdekat. Usaha pengarsipan visual dan tulisan ini tidak bisa kami lakukan sendiri, bagi kami ini adalah usaha kolektif. By the way, tidak semua hal harus dipandang dari kacamata komersil. Apa yang kami lakukan murni usaha menghibur diri.
Disclaimer, kami beberapa kali mendapatkan tawaran kolaborasi berbayar. Perlu diketahui bahwa uang yang kami terima dikembalikan kembali ke peserta dalam bentuk lain, makan siang misalnya.
Kita sering sekali menyederhanakan banyak hal, termasuk isu urban sosial. Kemiskinan tidak pernah romantis bagi kami, saya sendiri pernah bertahun-tahun memakan beras jatah raskin, dengan penghasilan under UMR Jogja yang you know lah. Jadi orang miskin buat saya ngga enak dan memang lebih ngga enak lagi kalo ada yang ngeliatin. Apa yang kami lakukan mungkin terlihat seperti memandang kemiskinan sebagai hal yang oke banget (((DIKONTENIN))), tetapi, coba dipertanyakan lagi, apakah gang selalu identik dengan kemiskinan? Nyatanya, dari temuan kami tidak selalu begitu. Tidak semua hal bisa dipandang hanya dari kacamata ibukota.
Salah satu trip yang kami lakukan adalah di kampung Badran, Yogyakarta. Kampung ini bertahun-tahun dikenal sebagai kampung preman. Preman paling preman di kampung lain, kalau sudah dihadapkan dengan preman Badran, pasti akan kicep. Urban legend ini hanya bisa diketahui oleh orang yang cukup lama tinggal di Jogja. Saya sendiri dulu takut hanya dengan melihat gerbang gang di kampung ini, tetapi di suatu ketika hal menggelitik terngiang di kepala saya,
“Apakah Badran masih seperti dulu, sementara kampungku sendiri mengalami banyak perubahan?”
Perjalanan pertama di kampung ini kami lakukan secara internal, dan apa yang kami jumpai justru berkebalikan dengan stereotype yang beredar dan mengakar di masyarakat Jogja. Kampung dan warga Badran sangat ramah, bahkan sekarang berubah menjadi kampung ramah anak.

Kami tidak puas dengan perjalan pertama. Di perjalanan kedua kami membersamai rekan dari komunitas Indonesia Graveyard, mereka adalah komunitas pengarsip makam-makam kuno. Bersama mereka, kami baru tahu kalau Badran dahulu adalah kompleks pemakaman Tionghoa. Di masa sekarang, bekas dari bongpay banyak tersebar di banyak titik di gang kampung ini. Kami memperoleh informasi lokasi juga tidak hanya dari pengamatan visual kami, tetapi juga berdasar dari penuturan warga sekitar. Dengan pemahaman baru ini, pencarian dan pendokumentasian bekas makam ini menjadi topik utama di hampir setiap perjalanan di kampung ini. Sampai saat ini (2023) ada 10 titik penemuan dengan belasan fragmen temuan.
Kami berusaha menghindari eksploitasi warga lokal dengan berusaha memberikan kontribusi yang mungkin tidak akan pernah sebanding dengan apa yang mereka berikan. Kami selalu memilih bisnis lokal sebagai titik kumpul, biasanya kedai kopi atau warung milik warga. Di dalam proses seleksi peserta, kami memberikan slot khusus bagi warga lokal (malah kalau bisa kami mencari warga yang mau join). Selain itu kami akan mengabarkan temuan menarik terkait sosial ekonomi daerah tersebut, bisa berbentuk (((KONTEN))) Instagram, maupun tulisan (yang agak jarang karena pasti jarang yang baca beginian). Kami selalu memberikan aturan main ketika hendak memulai petualangan seperti harap tidak terlalu berisik dan mengganggu warga, membawa uang jajan buat ngelarisi warung sekitar (ada warung gorengan di Badran yang enak banget tapi lupa namanya bu siapa), serta tentu saja bertegur dengan warga sekitar. Kami tidak mau berburuk sangka, kami meyakini siapapun pasti mengenal adab, pun ketika lalai, kita sama-sama punya kemampuan untuk saling menegur. Jadi apakah yang kami lakukan adalah sebuah eksploitasi kemiskinan? On your call.
Caranya join?
Tidak ada, kami bukanlah sebuah komunitas. Apa yang kami lakukan mungkin tidak jauh berbeda dengan rutinitas yang kamu jalankan. Kamu bisa melakukan apa yang kami lakukan sendiri di daerahmu. Kami adalah orang-orang malas, kami akan lebih senang jika kamu menjadi salah satu penyumbang (((KONTEN))). Kami akan lebih senang jika kamu bisa menceritakan apa yang menarik sekali dari daerahmu, sangat kami apresiasi jika ceritamu berbentuk tulisan, boleh panjang boleh tidak. Kami yakin ceritamu tidak semembosankan tulisan ini.
Nunggu kami kelamaan.